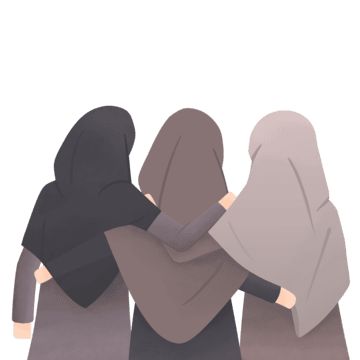Sebuah Cerpen oleh : Putri Nilam Sari
Malam semakin larut, hembusan angin semakin dingin menusuk ke tulang, aku masih setia menatap langit indah kota Kairo meskipun tanpa taburan bintang. Bertemankan secangkir kopi, aku berusaha melawan kantuk yang mulai menyerang, ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan diberi perhatian khusus, tapi otakku sudah tak bisa diajak bekerja sama, kebisingannya mengalahkan suara kendaraan yang berlalu lalang, bersahutan dengan suara suara pesawat yang mungkin melintas lima belas menit sekali, aku sudah kesulitan untuk fokus.
Ingatanku kembali pada pertama kali aku memutuskan untuk memilih jalan yang pada akhirnya mengantarku sampai ke titik ini, tidak mudah memang, banyak struggle dan ujiannya, jatuh bangun, penuh air mata, tak sekali dua nyaris menyerah, tapi itulah proses dan jalan yang aku pilih, bagaimanapun harus aku hadapi.
Dinginnya malam semakin menusuk, bersama sesal dan sesak yang memenuhi dada, air mataku jatuh basahi pipi, “ternyata aku sudah sejauh itu” pikirku.
Semangat yang dulu berkobar, perlahan semakin memudar, ayat demi ayat yang dulu aku perjuangkan mati-matian semua terasa samar dalam ingatan, menambah sesak di dada yang menyelimuti malam ini.
Teringat bagaimana dulu berjuang dan merayu untuk mendapatkan izin dari orang tua agar bisa menunda kuliah dan melanjutkan pendidikan ke sekolah non-formal dan harus masuk pondok lagi demi bisa fokus menghafal al quran, dimana saat itu pondok quran belum sebanyak yang sekarang, pendidikan non formal di nilai tak bisa menjamin masa depan, belum lagi aku berasal dari keluarga yang mementingkan pendidikan formal, yang tujuan akhirnya mendapatkan gelar, serta pekerjaan tetap di kantoran atau mengajar di sekolah. Tak sampai di situ, bahkan aku sampai dipanggil oleh bagian konseling sekolahku, menanyakan pilihanku yang tidak mau melanjutkan kuliah di tahun itu.
“Sayang banget, nilai kamu bagus, harusnya kamu bisa lanjut ke PTN pilihan, lagi pula setelah pendidikan non formal tersebut kamu mau bekerja dimana? Coba di pikir-pikir lagi?” nasihat guruku saat itu.
Aku juga kurang tahu itu sebuah nasihat atau apa, namun yang pasti pilihanku sudah bulat, aku tidak melanjutkan kuliah tahun itu. Aku tersenyum getir membayangkan semuanya, ternyata sudah sembilan tahun berlalu, dan nyatanya aku belum berhasil menjadi sebaik-baiknya penjaga kalamNya.
Tangisku semakin pecah, aku menyesalkan banyak hal.
“Sebegitu tidak pantasnya aku menjadi penjaga kalamya” lirihku.
***
Aku kembali berusaha untuk menghafalkan ayat demi ayat, mempersiapkan hafalan untuk disetorkan esok hari pada ustadz di sebuah markaz tahfizh dekat flat ku, aku berusaha mengumpulkan ingatan demi ingatan yang telah memudar, belum lagi harus mempersiapkan mental karena harus setoran dengan ustadz, yang biasanya aku setoran ke pada musyrifah atau ustadzah selalu ada feel yang berbeda, mentalku terlalu rapuh untuk bisa setoran ke ustadz.
Lagi-lagi aku berkelana pada ingatan saat masih berjuang di awal-awal menghafal, sistem pondok yang mengharuskan ujian kenaikan juz kepada pimpinan pesantren langsung, yang hafalan beliau selancar air mengalir, bahkan bisa menyimak dua sampai tiga orang sekaligus.
Aku ingat sekali, bagaimana dulu aku ujian juz 30, sampai mengulang ujian tiga kali, karena benar-benar dibaca dari awal juz hingga akhirnya, dengan maksimal salah tiga kali, tanpa bantuan sedikit pun. Aku yang baru mulai menghafal seusai SMA, dengan bacaan yang perlu di perbaiki, benar-benar tertatih dan pastinya sangat grogi.
Dulu, meski tertatih usaha untuk meraihnya tidak pernah berhenti, walau tak jarang penuh dengan airmata. Namun, kini semangat itu telah pudar, yang dibaca sama, yang dihafalkan sama, yang diperjuangkan sama, yang berbeda adalah semangatnya, Ghirohnya sudah tidak berapi-api seperti dulu lagi, aku merindukan aku yang dulu, aku ingin jatuh cinta sekali lagi dengan cinta yang sebenar cinta.
Editor: Fathiah Salsabila